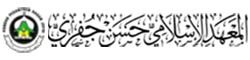Kisah Santri Nakal yang Pulang dengan Hati
Berubah
Di
sebuah pesantren sederhana, ada seorang santri yang terkenal “nakal”. Bukan
karena jahat, tapi karena sering melanggar aturan: telat jamaah, kabur ngaji,
dan lebih hafal jalan ke warung daripada jalan ke masjid. Namanya jarang
disebut saat doa bersama—lebih sering disebut saat laporan pelanggaran.
Suatu
malam, kiai memanggilnya. Bukan untuk dimarahi, tapi diminta menemani kiai
shalat tahajud. Santri itu bingung. Ia berdiri di belakang, canggung, sementara
kiai sujud lama—sunyi, khusyuk, seperti sedang berbincang dengan Allah.
Usai shalat, kiai berkata pelan,
“Ilmu itu bukan soal cepat atau lambat. Tapi soal mau pulang ke Allah atau
terus lari.”
Kalimat
itu menghantam lebih keras daripada hukuman apa pun. Malam itu, santri “nakal”
itu menangis—bukan karena takut, tapi karena sadar: ia lelah berlari.
Hari-hari
berikutnya, ia masih jatuh-bangun. Masih salah. Masih ditegur. Tapi satu hal
berubah: ia mulai pulang. Ke masjid. Ke kitab. Ke adab. Ke doa.
Bertahun
kemudian, orang-orang mengenalnya sebagai ustaz yang lembut pada santri
bermasalah. Katanya,
“Yang paling paham gelap, biasanya yang pernah.
Di pesantren, kadang yang tampak paling nakal justru sedang Allah
siapkan untuk pulang paling dalam.