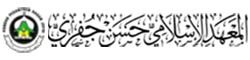Dulu, tangan ini tak pernah lelah menyuapimu.
Dada ini selalu menjadi tempat paling nyaman saat kau menangis ketakutan.
Langkah demi langkahmu yang pertama dulu kami sambut seperti prestasi dunia.
Dan malam-malam panjang yang kami habiskan tanpa tidur—bukan karena insomnia, tapi karena menjaga demammu agar tak semakin tinggi.
Kami tak pernah hitung semua itu sebagai pengorbanan. Itu cinta.
Tanpa pamrih.
Tanpa tanda jasa.
Dan tak pernah pula kami minta kau membalas.
Kami hanya berharap satu hal kecil: hormati kami, meski hanya dengan tutur katamu.
Tapi entah sejak kapan, nada suaramu mulai meninggi.
Kata-katamu mulai tajam.
Tatapanmu tak lagi penuh hormat, malah terasa mengintimidasi.
Dan kami hanya bisa diam—bukan karena takut, tapi karena tak ingin memperpanjang luka.
Kau tahu, Nak…
Lelah itu bisa hilang dengan istirahat. Tapi sakit hati karena dibentak anak yang dibesarkan dengan doa, itu sulit sembuhnya.
Kami bukan malaikat yang tak pernah salah.
Kami hanya orang tua yang ingin yang terbaik untukmu, dengan cara yang mungkin tak selalu kau suka.
Tapi kami tak pernah ingin jadi musuhmu.
Kami hanya ingin tetap jadi tempat pulang, bukan yang kau tinggalkan dengan nada tinggi dan wajah kesal.
Jika hati ini kadang diam, itu bukan karena tak merasa. Tapi karena kami memilih menangis dalam sujud agar kau kembali.
Jika tangan ini tak lagi menegurmu, bukan karena tak peduli, tapi karena khawatir kata kami justru membuatmu makin jauh.
Wahai anakku…
Jangan tunggu doa kami berubah menjadi luka yang naik ke langit.
Jangan tunggu waktu memisahkan kita lalu kau berkata: "Andai aku bisa minta maaf sekali lagi."
Datanglah…
Peluk kami.
Katakan bahwa hatimu masih punya ruang untuk mendengarkan kami—bukan membentak.
Sebab ketika kamu benar-benar kembali dengan hati yang tunduk, kami tak akan mengingat lukamu. Kami hanya akan memelukmu lebih erat dari sebelumnya.