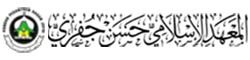Namanya
Amar. Usianya belum genap sepuluh tahun. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah
desa kecil di pinggiran kota. Ayahnya telah wafat ketika ia masih balita. Sejak
itu, ibunya menjadi segalanya bagi Amar—tempat berlindung, belajar, sekaligus
pengganti tangan ayah yang hilang.
Menjelang
Idulfitri, semua anak-anak di kampungnya bersorak gembira. Baju baru, sepatu
mengkilap, kue-kue yang menumpuk. Tapi tidak bagi Amar. Ia masih mengenakan
sandal usang, baju warisan dari kakaknya, dan belum satu pun kue tersaji di
meja rumahnya.
Suatu
malam, ia mendekati ibunya dan bertanya pelan, “Bu, nanti waktu salat Ied… Amar
boleh ikut, kan?”
Ibunya
mengangguk, meski hatinya pilu. Ia tahu, anaknya pasti malu karena tak punya
baju atau sandal baru seperti teman-temannya. Tapi Amar tak mengeluh. Ia hanya
ingin ikut mencium tanah di pagi hari raya, sebagaimana dulu ia lihat ayahnya
melakukannya.
Keesokan
harinya, ibu Amar terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengeluarkan selembar
uang terakhir yang terselip di dalam mukena—uang yang tadinya ingin ia simpan
untuk membeli beras. Tapi demi melihat wajah anaknya bersinar walau hanya
sebentar, ia berjalan kaki ke pasar dan membeli sepasang sandal plastik
berwarna biru.
Ketika
Amar bangun dan melihat hadiah kecil itu, matanya berkaca-kaca.
“Ini…
buat Amar, Bu?”
Ibunya
tersenyum dan mengangguk. “Selamat lebaran, Nak.”
Hari
itu, Amar berjalan ke masjid dengan penuh rasa bangga. Sandalnya mungkin murah,
bajunya mungkin lusuh, tapi hatinya… lebih megah dari istana.
#Anak yatim bukan hanya butuh bantuan, tapi juga butuh penghargaan dan cinta. Kadang, sepasang sandal sederhana bisa menjadi hadiah paling mulia jika diberikan dengan penuh kasih sayang.