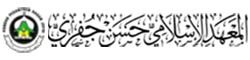Di sebuah pondok sederhana, hiduplah seorang santri bernama Fikri. Ia berasal dari keluarga miskin di desa terpencil. Setiap kali tiba waktu pembayaran uang bulanan, hatinya selalu bergetar. Ia tahu, ibunya pasti sedang berusaha keras di rumah—menjual sayur, mencuci pakaian orang, bahkan kadang menahan lapar—hanya agar Fikri bisa terus mondok.
Suatu hari, Fikri menerima surat dari ibunya. Hanya selembar kertas lusuh yang diselipkan bersama selembar uang sepuluh ribu. Tulisan di dalamnya sederhana:
“Nak, Ibu nggak punya apa-apa lagi. Tapi jangan berhenti belajar. Kalau kamu bisa jadi orang baik dan berilmu, itu sudah cukup membuat Ibu kaya.”
Air mata Fikri jatuh membasahi surat itu. Malam itu, ia berdoa lama sekali. Ia tidak meminta kekayaan, tidak juga kemudahan hidup. Ia hanya berkata lirih:
“Ya Allah, jagalah ibuku. Jadikan ilmu ini sebagai jalan untuk membahagiakannya.”
Beberapa tahun berlalu. Fikri lulus, dan kini menjadi guru di pesantren tempat ia dulu menimba ilmu. Suatu pagi, ia kembali ke desa. Ia membawa sesuatu untuk ibunya — bukan uang banyak, bukan emas, hanya satu hal: segelas air zamzam.
Ia berkata pelan, “Bu, dulu Ibu kirim saya segelas air perjuangan. Sekarang biar saya kembalikan segelas air doa.”
Ibunya menangis. Dan di antara air mata itu, mereka sama-sama tahu: perjuangan tak pernah sia-sia.